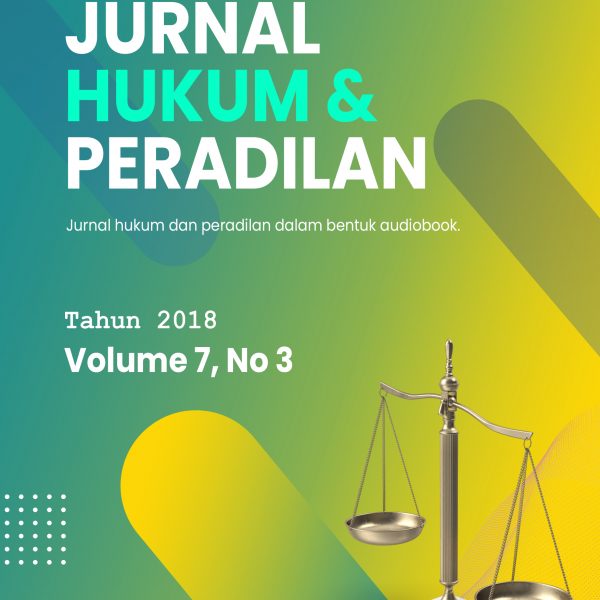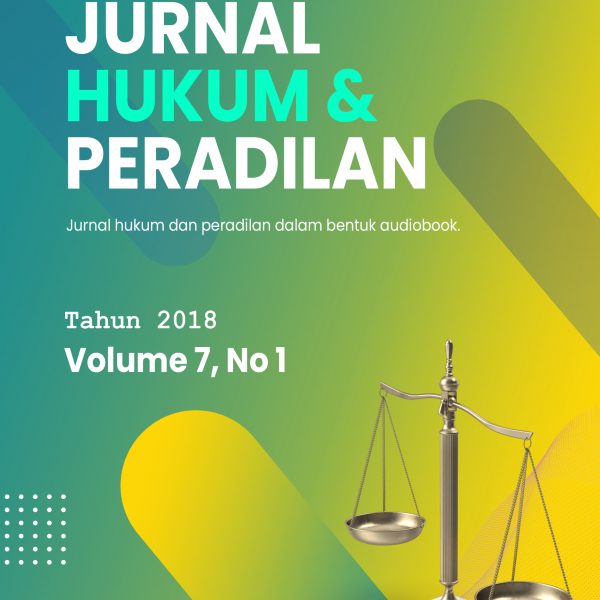Jurnal Tahun 2018
Volume 7, No 2
Abstrak.
Pada masa sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, sikap PTUN terhadap sengketa Pilkada sangat beragam mulai dari tidak lolos dismisal, lolos dismissal tetapi ditolak atau dinyatakan tidak diterima (N.O.) oleh Majelis Hakim, bahkan ada yang gugatan dikabulkan. Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 junctis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sikap PTUN hanya 1 (satu) dan sangat tegas yaitu menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Pilkada. Dinamika dan perubahan sikap PTUN tersebut dikarenakan adanya perubahan keadaan hukum dan maksud-maksud lain, yaitu PTUN ingin memaksimalkan lembaga-lembaga yang nyata-nyata diberi wewenang untuk menyelesaikan sengketa pada setiap tahap mulai dari sengketa administrasi sampai dengan sengketa hasil, menghindari disparitas putusan PTUN dengan putusan MK, membangun budaya hukum masyarakat yang siap menang dan siap kalah, serta menghindari sengketa yang berkepanjangan yang menghabiskan banyak tenaga, waktu, dan biaya.
Abstrak.
UUD Tahun 1945 Pasal 18B ayat (1) memberikan legitimasi terhadap Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh yang merupakan hasil kesepakatan Pemerintah Indonesia dengan GAM. Hal ini kemudian dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Permasalahannya ialah bahwa materi Qanun tersebut dianggap bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007. Pemerintah Pusat menghendaki perbaiki terhadap beberapa materi Qanun tersebut, namun pihak Pemerintah Aceh hal dianggap menyalahi MoU Helsinki. Hasil penelitian sebagai berikut: Pertama, menemukan landasan pemikiran lahirnya Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh terdiri dari Pasal 18B UUD Tahun 1945 serta perumusan Pasal 246 dan Pasal 247 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Kedua, bahwa akibat hukum dari adanya Pasal 246 dan Pasal 247 berlaku dan sah untuk diterapkan melalui pembentukannya Qanun Aceh. Ketiga, konsekuensi yuridis adanya Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 berlaku secara yuridis dan dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Aceh karena sudah diundangkan dalam lembaran daerah. Disarankan pihak kalangan akademis, pemangku jabatan yakni Pemerintah Aceh, DPRA dan Pemerintah Pusat untuk memperjelas dan memberi kepastian kepada rakyat Aceh supaya tidak Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tidak dijadikan komoditas politik pada saat-saat tertentu. Kemudian dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 perlu ditinjau ulang terkait pemaknaan terhadap bendera dan Lambang Aceh.
Abstrak.
Diskresi sebagai wewenang bebas, keberadaannya rentan akan disalahgunakan. Penyalahgunaan diskresi yang berimplikasi merugikan keuangan negara dapat dituntutkan pertanggungjawabannya secara hukum administrasi maupun hukum pidana. Mengingat selama ini peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak merumuskan secara rinci yang dimaksudkan unsur menyalahgunakan kewenangan maka para hakim menggunakan konsep penyalahgunaan wewenang dari hukum administrasi. Problema muncul saat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dimana telah memicu persinggungan dalam hal kewenangan mengadili penyalahgunaan wewenang (termasuk diskresi) antara Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pada perkembangannya, persinggungan kewenangan mengadili tersebut ditegaskan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 bahwa PTUN berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penilaian ada atau tidak ada penyalahgunaan wewenang (termasuk diskresi) dalam Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan sebelum adanya proses pidana. Sehubungan tidak dijelaskan tentang definisi dan batasan proses pidana yang dimaksud, maka timbul penafsiran yang berbeda. Perlu diadakan kesepakatan bersama dan dituangkan dalam regulasi tentang tapal batas persinggungan yang jelas tanpa meniadakan kewenangan pengujian penyalahgunaan wewenang diskresi pada Pengadilan TUN.
Abstrak.
Dalam UUAP (Undang-Undang Administrasi Pemerintahan), penyalahgunaan wewenang merupakan genus yang terdiri dari tiga spesies yang berbeda-beda yakni (1) melampaui wewenang; (2) mencampur-adukan wewenang; (3) bertindak sewenang-wenang. UUAP tidak menjelaskan pengertian penyalahgunaan wewenang, ia hanya mengkualifikasi ke tiga jenis spesies penyalahgunaan wewenang sebagaimana disebut di atas. Dikaitkan dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun) dalam menguji penyalahgunaan wewenang vide pasal 21 UUAP haruslah dilihat dalam konteks yang terbatas yakni semata dalam aspek pengujian penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Pengujian penyalahgunaan wewenang dalam aspek bersifat parsial dan sangat terbatas jika dibandingkan dengan luasnya ruang lingkup dan kompleksitas pengertian penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi.
Abstrak.
Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender sudah menjadi sebuah gerakan berbahaya, akan tetapi belum ada norma hukum yang mengatur tentang perilaku asusila tersebut, Pentingnya sanksi terhadap pelaku zina dan LGBT merupakan bentuk ketegasan negara dalam melindungi moral dan ideologi Nusantara dari faham berbahaya, akan tetapi Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan tersebut karena pemidanaan pelaku zina, baik strafsoort maupun strafmaat, dan perilaku asusila lesbian, gay, biseksual, dan transgender memerlukan pembentukan norma baru, sehinggga menjadi Kebijakan hukum pidana (Penal policy). Kewenangan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, akan tetapi menjadi hak Pembentuk Undang-Undang yaitu DPR bersama Presiden. Tulisan ini merupakan Anotasi atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUUXIV/2016 yang memberikan penjelasan kepada masyarakat adanya Quo Vadis Kebijakan hukum pidana (Penal policy) dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.
Abstrak.
Artikel ini mengkaji mengenai independensi kekuasaan kehakiman yang ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi. Independensi kekuasaan kehakiman merupakan keharusan dalam sebuah negara hukum (rechtstaat). Negara hukum baik dalam konsep Rule of Law ataupun Rechtstaat, menempatkan peradilan yang bebas dan tidak memihak (independence and impartiality of judiciary) sebagai salah satu cirinya. Akan tetapi, kemerdekaan tersebut bukanlah tanpa batasan sehingga dapat diterjemahkan dengan seluas-luasnya. Sering kali dalam praktiknya independensi didalilkan untuk berlindung atas suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya, perlu dilakukan penggalian makna independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana amanat Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Oleh karenanya, pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi terkait putusan-putusan yang menjadikan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai batu uji dalam pengujian undang-undang layak untuk dikaji dan diangkat menjadi tafsiran mengenai makna independensi kekuasaan kehakiman. Tulisan ini menggali pandangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang memuat pertimbangan mengenai independensi kekuasaan kehakiman. Penulisan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Tulisan ini menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primernya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi. Data dianalisis menggunakan metode kualitatif.
Abstrak.
Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Ratio legis-nya adalah mewujudkan kepastian hukum dan keadilan melalui asas peradilan cepat, tepat, adil dan murah. Eksistensi PHI menimbulkan masalah, baik kemampuan pengetahuan pekerja/buruh tentang hukum formil maupun hukum ketenagakerjaan materil, proses lama, dan substansi hukum belum memadai. Tinjauan ini urgen dilakukan untuk identifikasi upaya yang dapat dilakukan agar ratio legis eksistensi PHI terwujud. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan didasarkan pada pengkajian hukum positif, yaitu UU No. 2 Tahun 2004. Pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan untuk mengkaji asas-asas peradilan. Hasil tinjauan ini mengidentifikasi beberapa kelemahan, baik dari segi struktur hukum, substansi dan budaya hukum. Upaya untuk mengatasinya, yakni dengan membentuk PHI di setiap Pengadilan Negeri Kabupaten/Kota. Revisi UU No. 2 Tahun 2004 yakni : pengaturan yang memperluas pengertian subjek hukum pekerja/buruh dan pengusaha; lembaga konsiliasi dan arbitrase dipertimbangkan keberadaannya; pengaturan upaya hukum kasasi yang nilai gugatannya di bawah Rp.150 juta dihapus; pengaturan pailit dikategorikan sebagai keadaan mendesak dalam pemeriksaan acara cepat sinkron dengan ketentuan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; pengaturan khusus mengenai eksekusi putusan PHI dan pengaturan tidak memperkenankan upaya hukum PK dalam proses eksekusi. Kepastian hukum batas waktu proses administrasi perkara hingga pelaksanaan putusan. Optimalisasi pemanfaaatan sarana Informasi Teknologi (IT) dalam proses administrasi perkara, khususnya pemanggilan “delegasi”.
Abstrak.
Munculnya fallacy argumentum ad verecundiam dalam suatu putusan pengadilan merupakan suatu penalaran hukum yang tidak tepat, oleh karena penggunaan otoritas yang tidak dapat dibenarkan berdasarkan Ilmu Hukum, akan berakibat kepada validitas dari amar putusan—yang merupakan konklusi, yang dapat dibatalkan. Sifat pembatalan amar putusan tersebut bukanlah disebabkan karena amar putusannya yang tidak tepat, namun dikarenakan sumber logika yang digunakan adalah tidak tepat.